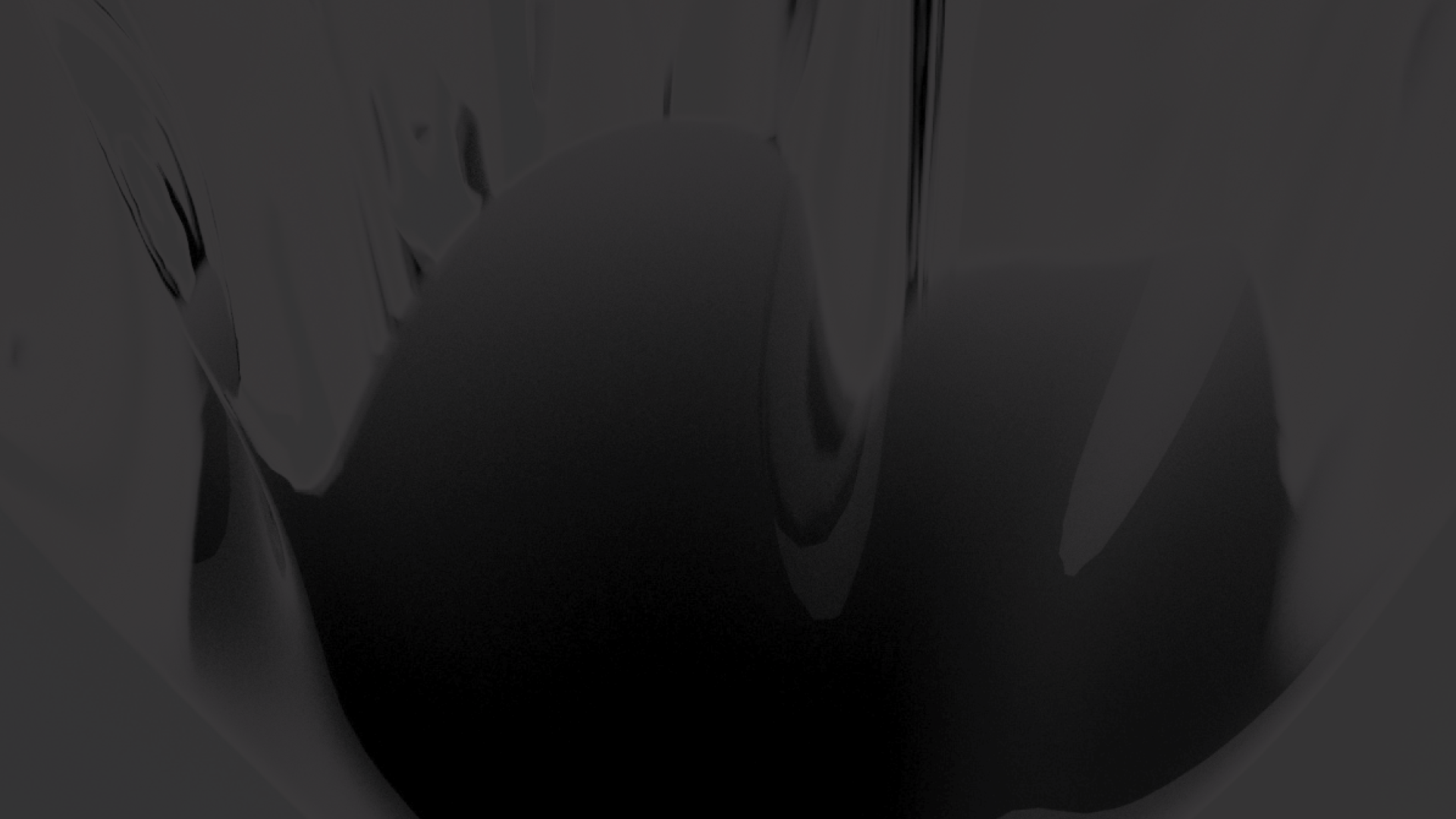Panggilan Terbuka Kusala Sastra Khatulistiwa 2026
Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) merupakan penghargaan sastra bergengsi yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Dilaksanakan pertama kali pada tahun 2001 oleh Richard Oh dan kawan-kawan dengan nama Khatulistiwa Literary Award, penghargaan ini hadir sebagai ruang apresiasi bagi karya-karya sastra Indonesia yang menandai zamannya. Sejak tahun 2014, penghargaan ini berganti nama menjadi Kusala Sastra Khatulistiwa, sebagai upaya memperkuat identitas serta konsistensi penggunaan bahasa Indonesia. Selama lebih dari dua dekade, KSK telah mengangkat dan mengapresiasi karya para penulis terkemuka yang memperkaya tradisi prosa maupun puisi Indonesia.
Untuk menjaga kesinambungan penghargaan ini setelah wafatnya Richard Oh pada tahun 2022, keluarga bersama para sahabat dekat kemudian mendirikan Yayasan Richard Oh Kusala Indonesia (YRKI) pada tahun 2024. Yayasan ini mengemban mandat untuk meneruskan semangat filantropis dan kecintaan Richard Oh terhadap sastra Indonesia, sekaligus menjadi penyelenggara Kusala Sastra Khatulistiwa. Dalam pelaksanaannya, YRKI didampingi oleh tiga orang kurator, yaitu Eka Kurniawan, Hasan Aspahani, dan Nezar Patria, yang menjalankan peran strategis dalam merancang program, mendampingi proses penyelenggaraan, serta menentukan dewan juri.
Dengan dukungan Dana Indonesiana serta sejumlah mitra lain, Kusala Sastra Khatulistiwa kembali diselenggarakan pada tahun 2025. Pada edisi tersebut, penghargaan diberikan dalam tiga kategori, yaitu kumpulan cerpen, novel, dan kumpulan puisi. Adapun para pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa 2025 adalah:
- Kategori Kumpulan Cerpen: Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-kupu karya Sasti Gotama
- Kategori Novel: Duri dan Kutuk karya Cicilia Oday
- Kategori Kumpulan Puisi: Hantu Padang karya Esha Tegar Putra
Keberhasilan penyelenggaraan tahun 2025 menandai babak baru dalam sejarah Kusala Sastra Khatulistiwa, sekaligus mempertegas posisinya sebagai ajang penghargaan yang tidak hanya mengapresiasi karya sastra terbaik, tetapi juga berupaya memperluas jangkauan pembaca melalui program literasi yang lebih inklusif.
Memasuki tahun 2026, Yayasan Richard Oh Kusala Indonesia kembali menyelenggarakan Kusala Sastra Khatulistiwa sebagai kelanjutan dari komitmen untuk menghadirkan penghargaan sastra yang berkesinambungan. Penyelenggaraan tahun ini diharapkan tidak hanya melanjutkan tradisi yang telah terbangun, tetapi juga semakin memperkuat peran KSK dalam ekosistem kesusastraan Indonesia di masa mendatang.
Dengan ini, YRKI secara resmi mengumumkan syarat dan ketentuan penyelenggaraan Kusala Sastra Khatulistiwa 2026. Informasi lain mengenai hadiah, Daftar Panjang, Daftar Pendek, dan lain-lain akan disampaikan dalam pengumuman berikutnya.
Syarat dan Ketentuan
- Terbuka bagi penulis berkewarganegaraan Indonesia. Karya yang diajukan merupakan hasil karya penulis tunggal dan tidak melanggar hak cipta.
- Karya yang diajukan berupa buku cetak yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2025.
- Karya ditulis dalam bahasa Indonesia.
- Tiga kategori karya:
-
- Kumpulan cerpen, dengan jumlah minimal dua cerpen.
- Novel, dengan panjang minimal 30.000 kata.
- Kumpulan puisi, yang terdiri dari minimal 40 puisi, atau 40 halaman, atau satu puisi panjang dengan total minimal 40 halaman.
- Penerbit atau penulis mengirimkan setidaknya dua eksemplar dari setiap judul karya yang diajukan. Pengiriman disertai dokumen pendukung berupa biodata penulis dan mencantumkan informasi kontak.
- Karya dikirimkan paling lambat tanggal 28 Februari 2026 (cap pos). Karya dikirimkan ke:
Kusala Sastra Khatulistiwa 2025
ED Cluster No. 2A
Jalan Gunung Indah V
Cirendeu, Ciputat Timur,
Tangerang Selatan, Banten
15445
- Daftar panjang dan daftar pendek karya terpilih diumumkan sebelum pengumuman pemenang.
- Pengumuman pemenang akan dilakukan pada acara Malam Anugerah Kusala Sastra Khatulistiwa 2026.
Narahubung
Email: info@kusala.id
Laporan Dewan Juri Kusala Sastra Khatulistiwa 2025
Dewan Juri Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) 2025 yang dibentuk oleh penyelenggara telah bekerja maksimal dan sungguh-sungguh berdasarkan penghayatan, pengetahuan, dan pengalaman bergumul dengan karya sastra dan pengetahuan sastra. Dalam menilai dan memutuskan karya sastra mana yang terpilih dalam daftar panjang, kemudian daftar pendek, dan akhirnya pemenang, Dewan Juri bersepakat mengedepankan penilaian-penilaian kepakaran (expert judgmental) yang didasarkan pada pengalaman panjang dan pengetahuan mencukupi di bidang karya sastra.
Selain itu, Dewan Juri juga bersepakat bahwa pertama-tama pembacaan dan penilaian berpusat pada teks, pada karya sastra, bukan pada pertimbangan gender, domisili sastrawan, penerbit, dan sebagainya. Kedaulatan dan otonomi teks sastra menjadi fokus utama, kemudian baru fokus intertekstualitas baik sinkronis maupun diakronis.
Lebih lanjut, Dewan Juri bekerja secara personal dan kolektif untuk memutuskan manakah karya-karya sastra yang lolos daftar panjang, daftar pendek, dan kemudian pemenang. Pada taraf personal, masing-masing juri menghayati, memahami, mencermati, menanggapi, dan menilai karya-karya sastra yang terbit tahun 2024 yang diterima oleh panitia maupun yang dipantau oleh Dewan Juri. Hasilnya kemudian didiskusikan secara kolektif dalam forum-forum pertemuan yang digelar untuk menilai dan memutuskan karya sastra mana yang layak lolos daftar panjang, daftar pendek, dan lalu pemenang. Dengan cara demikian, penilaian dan pengambilan keputusan mana karya sastra yang masuk daftar panjang, daftar pendek, dan lalu pemenang memenuhi standar intersubjektivitas yang biasa digunakan dalam dunia humaniora.
Secara lebih spesifik, penghargaan karya sastra terbaik sepanjang tahun 2024 ini difokuskan untuk memilih karya-karya yang menunjukkan pengerahan kerja kreatif sastrawan Indonesia, pengembangan potensi estetis dalam penggunaan bahasa Indonesia, dan perluasan kemungkinan wilayah pertemuan antara imajinasi dan realitas.
KEMBALI KEPADA HAKIKAT CERPEN
Dunia terus bergerak, Bumi konsisten berputar mengayuh waktu. Memang demikianlah hukum rotasi alam semesta bagi semua planet termasuk yang kita huni selama ini. Oleh karena itu, ketika peradaban beranjak maju, kadang-kadang menemu siklus, seolah-olah blue print kehidupan selain linier juga spiral. Hal itu berlaku hampir untuk semua peristiwa sembari melahirkan sesuatu yang (mungkin) baru. Di sisi langkah kita, peribahasa klise kerap mengganggu: tidak ada yang betul-betul anyar di bawah matahari.
Dalam pencarian satu bidang seni saja, dalam hal ini sastra, kami belum tentu menemukan. Saat kami menemukan karya cipta dengan batasan kurun waktu singkat—setahun saja—tidak dapat dipastikan bahwa itu yang kami cari. Namun, alangkah repot dan naif bila semua unsur harus menjadi penghalang kehadiran anak kreatif yang mungkin merupakan perasan pikiran, spiritual, pengalaman, dan keterampilan bagi rahimnya. Berbeda dengan kelahiran bayi biologis yang bergantung kepada Takdir (t besar), munculnya karya sastra seolah-olah diatur oleh takdir (T kecil) lain. Pengarang bisa atau boleh menjadi tuhan meski beberapa pujangga juga menyebutkan bahwa inspirasi dan gagasan menggerakkan tangannya untuk menuliskan peristiwa—seakan-akan tanpa ia sadari.
Lima kumpulan cerpen yang kelak harus kami pilih satu di antara mereka sebagai yang “terbaik” semoga memenuhi kriteria secara umum kendati tidak semua pembaca—tentu saja termasuk dewan juri—memiliki selera yang sama. Justru keberagaman pandangan, layaknya rahmat, memberi kami kekayaan batin dan pikir satu sama lain. Perdebatan sejak awal sudah terjadi untuk mendapatkan mula-mula sepuluh dari sekian yang kami baca, tetapi bukan pertengkaran yang kami cari. Pandangan lazim dan argumentasi yang saling menonjok, ternyata mirip batu asah yang sedang menyigar dan memangkas intan untuk menjadi berlian.
Kini tersisa—lebih tepat terwakili—lima kumpulan cerpen dengan menepikan persoalan gender dan geografis para penulisnya. Kami memilih melalui pengamatan yang fokus terhadap teks karena ini karya sastra yang semestinya melingkupi perkara antara lain gagasan dan cara bertutur yang ditawarkan, percobaan yang diupayakan, dan pijar kacil yang menggugah kesadaran kami untuk mengatakan bahwa ini elok. Apakah elok yang kami maksud merupakan gabungan antara etik, estetik, eksotik, dan eklektik? Bisa ditafsir demikian walau dalam penilaian karya seni, tidak ada bungkus yang tepat dan memadai selain pertanggungjawaban sewaktu-setempat yang diharapkan kokoh dan dipercaya.
Kehadiran para pengarang “baru” seperti kebetulan mengisi ruang kompetisi dan itu menarik perhatian kami. Setidaknya kami mengamati karya-karya yang melepaskan diri dari epigonisme sekaligus memberikan percik asyik. Giringan pembacaan itu membawa kami untuk memasuki ruang renung yang berbeda, kegelisahan yang lain, gaya berdongeng yang tidak diikat kaidah-kaidah lama. Seiring teknologi yang seolah-olah melompat sejak kedatangan internet dan difungsikan secara mau-tak-mau sepanjang pandemi Corona, jaringan pun meluas dengan sendirinya. Kegelisahan atau ruang renung yang semula privat dikobarkan dengan melepaskan diri dari personalitas menuju universalitas. Mungkin masing-masing pengarang sedang dirundung kutuk untuk segera menuangkan gagasan dalam teks sehingga yang monofonik berubah menjadi polifonik.
Membincang tema, pada dasarnya semua berangkat dari “aku” yang mewakili masyarakat atau karakter komunal. Kemudian, satu demi satu melangkah pada tradisi tertentu, mengulik kesehatan mental, persoalan unik dialektika, harapan yang sebagian besar masygul, absurditas justru tentang realita yang kadang-kadang melampaui fantasi. Ketika menghadapi kondisi—di luar situasi politik—yang rumit itu membuat para pengarang membuka gembok katarsis, kami ingin menggarisbawahi: inilah kekinian yang sedang berlangsung.
Iblis Tanah Suci karya Arianto Adipurwanto menyajikan berbagai titik nadir manusia dalam suatu masyarakat yang masih meyakini mitos terkait roh leluhur. Dua wilayah dimensi yang berbeda diibaratkan ruang ulang-alik yang setiap pribadi boleh menyatakan sebagai kebenaran. Kesengsaraan tampak sangat lugas, bahkan negara seperti tidak hadir dalam ranah itu. Sementara itu, Keluarga Oriente karya Armin Bell memutar lensa zoom in untuk mendapatkan kisah-kisah setengah heroik dalam lokasi kecil. Ada unsur parodi yang penulisnya—sebagaimana syarat seorang komika—"tidak boleh ikut tertawa”. Ironisme hadir begitu halus tertutup oleh kesederhaannya bertutur dengan liku-liku yang strategis dan simpulan untuk terperangah.
Dalam Mei Salon karya Iin Farliani, tampak cerita-cerita serupa biji jagung yang ditebar di hamparan tanah, meluncur ke sana-kemari. Yang semula dalam genggaman, bisa berakhir di utara atau barat, sebelum pelbagai burung (pembaca) mematukinya. Sebetulnya kehidupan yang panjang bagi setiap insan, ada kalanya mendapati episode tidak memiliki tujuan atau sedang sangat peduli terhadap keadaan sosial di sekitarnya. Kepedulian yang boleh jadi mengusik kemerdekaan pribadi di tengah tarik-menarik kepentingan itu mengakibatan mental kita terganggu. Dengan memasuki dan memerankan tokoh yang tidak selalu manusia, Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu karya Sasti Gotama menyodorkan semacam kertas kerja atas pasien yang tidak tahu apa penyakitnya. Gaya tuturnya memberi warna baru dengan menyediakan labirin dalam plot yang secara umum perlu dibaca ulang. Di akhir kisah tercantum twist yang menyaru. Sang penulis demikian detail menggambarkan perangkat dalam pokok pembicaraan, juga menjuluki para tokoh sesuai karakternya.
Satu-satunya yang sudah mengarungi pengalaman panjang dalam dunia penulisan adalah Kiki Sulistyo dengan kumpulan cerpen Musik Akhir Zaman. Soal kepiawaian mengolah ide dan menyajikan sebagai menu spesial di meja makan—yang wadag atau maya—masih bertahan. Harmoni antara realisme dan surealisme kadang-kadang mendedahkan kritik simbolik terhadap kemapanan keyakinan, termasuk sisipan tragedi masa lalu yang memang tidak tuntas sebagai bahan pembicaraan. Saat bermain memindahkan point of view, misalnya, membuat kami seperti sedang melihat karya seni psikologis.
Dari daftar pendek berupa lima kumpulan cerpen tersebut, tanpa sengaja kami bagai kembali kepada prinsip cerita pendek yang memang pendek. Mengapa cerpen harus panjang seolah-olah berkhianat terhadap “rukun”-nya kemudian dibuat istilah cerpen panjang atau setenag novela? Dengan keterbatasan ruang, bahkan untuk media massa cetak, seolah-olah hal itu menjadi rintangan. Namun, seorang cerpenis tidak boleh kehilangan daya. Dengan kebiasaan para pembaca instan dan penganut iformasi digital, medium pun berubah. Kini, bukan hanya soal ruang, melainkan mereka juga bertarung dengan waktu. Maka wajar jika penulis cerpen yang “pintar” akan mengambil peluang jitu memburu pembacanya dengan kisah-kisah ringkas. Dengan demikian pemeo lawas bahwa “cerpen habis dibaca dalam sekali duduk” sungguh menjadi tantangan. Bagaimana taktiknya? Misalnya dengan memperkecil jumlah konflik, mengurangi tokoh, membatasi paparan yang tidak berguna …. Ahai, tentu ini bukan nasihat dewan juri tahun ini yang sekali waktu mengalami hal yang sama dalam menulis cerpen.
Buku kumpulan cerpen terbaik yang kami pilih mahir meramu ironi guna menyoroti masalah-masalah kesehatan mental ataupun menyingkap sisi lain dari realitas. Masing-masing cerita memiliki pusat yang tidak selalu manusia dan oleh karena itu menghadirkan dunia yang unik. Ketelitian penulis tampak dalam ketangkasannya menggunakan bahasa, latar, dan konflik yang taut-menaut membangun dunia dalam cerpen-cerpennya.
TEKS PANJANG NOVEL
PADA ERA KESINGKATAN DAN MYSIDE THINKING
Zaman kontemporer adalah zaman yang menawarkan kesingkatan, termasuk terkait teks, dan tradisi myside thinking, kegemaran untuk ikut-ikutan berpendapat tanpa menimbang kepakaran. Ditarik ke ranah produksi teks kreatif, dua karakteristik itu sepintas tampak menyusun ekosistem yang tidak mendukung produksi novel. Karakteristik pertama bertentangan dengan karakteristik novel sebagai satu tipe teks fiksi yang identik dengan naratif panjang. Karakteristik kedua bertentangan dengan karakteristik novel sebagai satu tipe teks fiksi yang menuntut keutuhan tematis, satu hal yang hanya dimungkinkan oleh penguasaan atas tema itu sendiri.
Lantas, kita mungkin bertanya-tanya seperti apakah nasib novel dalam situasi semacam itu? Berdasarkan jumlah novel yang masuk ke dalam seleksi awal Kusala Sastra Khatulistiwa 2025 maka kita mendapatkan perkiraan kasar bahwa sepanjang tahun 2024 terbit 6 novel tiap bulan, jumlah yang sedikit lebih banyak dari antologi cerpen, tetapi lebih sedikit dari antologi puisi. Tentu ada banyak faktor lain yang memengaruhi komparasi tersebut, tetapi setidaknya bisa kita katakan bahwa iklim kegandrungan akan kesingkatan ternyata tidak banyak memengaruhi ekosistem tempat para novelis kita bekerja.
Pengaruh itu mungkin justru lebih tampak dalam karakteristik yang kedua, penguasaan novelis akan tema yang disodorkan dalam novel. Penguasaan atas apa yang disodorkan, sebagaimana juga penguasaan atas naratologi, cara menyodorkan naratif, tidak selalu tampak pada novel-novel yang tercantum dalam daftar novel masuk untuk diseleksi oleh dewan juri Kusala Sastra Khatulistiwa 2025. Kelima novel yang kami pilih sebagai Daftar Pendek ini merupakan novel-novel yang setelah melalui perdebatan panjang kami putuskan paling memenuhi timbangan kami terkait kesegaran, kreativitas berbahasa, dan potensi nilai pentingnya sebagai satu teks sastra.
Novel pertama, BEK karya Mahfud Ikhwan, menyajikan kekhasan tema yang disampaikan dengan gaya bahasa naratif pengarangnya yang juga tidak kalah khas, mencerminkan pergulatan panjang pengarangnya dengan dunia prosa. Novel ini tampak hadir pertama-tama sebagai novel, yakni prosa yang, dengan mode perlokusi, mencoba memantik kenikmatan pembaca melalui naratif, melalui keprigelan pengarangnya menggunakan bahasa. Akan tetapi hal tersebut bukan menandakan bahwa novel ini jatuh menjadi sekadar prosa hiburan, melainkan justru sebaliknya, isu-isu penting yang tidak pernah lekang dari hidup, semisal isu ekonomi, hadir terselip dengan natural sehingga menciptakan komposisi holistis sebuah novel, padu antara bentuk dengan konten.
Dengan gaya berbeda dari BEK, Duri dan Kutuk karya Cicilia Oday menampilkan kisah yang menempatkan jelajah batin karakter-karakternya sebagai poros. Kesegaran hadir dalam kemungkinan tautan antara kisah tersebut dengan gema teori sastra Ekokritik dan lebih spesifik lagi Ekofeminisme. Tautan dengan teori-teori terbaru dalam Ilmu Sastra tersebut, berbeda dengan yang ditemukan dalam apa yang lazim disebut sebagai sastra bertendens, bukan hadir secara terang-benderang melainkan hanya mungkin hadir setelah melalui penapisan cermat di sela kenikmatan jelajah naratif.
Dua novel selanjutnya, Matthes karya Alan Th dan Paya Nie karya Ida Fitri, secara khusus memosisikan sejarah sebagai urat tunggang, satu upaya yang membutuhkan keprigelan tersendiri karena terpeleset sedikit saja akan menjatuhkan teks novel menjadi hanya pengulangan teks sejarah. Sejarah dalam Matthes bertolak dari sejarah teks-teks klasik, terutama I La Galigo, sebuah teks tentang teks. Naratif kemudian bergerak menghasilkan jahitan rapi dengan berbagai isu yang kerap luput dalam pembicaraan sejarah, termasuk gairah penemuan sampai penerjemahan teks terkait pada periode yang jauh. Dibaca pada masa kini, elaborasi semacam itu bisa menjadi semacam pengingat pada kerja pengarsipan teks kesusastraan kita yang pernah dilakukan dengan tekun oleh H.B. Jassin sekaligus sindiran halus betapa semakin memudarnya gairah semacam itu seiring terjadinya pergantian generasi.
Adapun novel Paya Nie bertolak dari peristiwa besar yang mengendap sebagai memori perjumpaan paksa dan tragis antara penduduk sipil dan militer di Aceh. Endapan senada memang sudah berkali-kali muncul sepanjang dua dekade terakhir kesusastraan kita, baik berupa letupan ataupun bisikan, baik dalam bentuk puisi ataupun terutama prosa. Akan tetapi Paya Nie memiliki kekhasan naratif berupa percampuran lokalitas dengan keindonesiaan yang natural serta penempatan perempuan dan anak-anak sebagai poros naratif, dua pihak yang kerap terabaikan dalam narasi-narasi rekaman gemuruh konflik bersenjata yang cenderung bersifat falik.
Terakhir, Oni Jouska karya Asep Ardian adalah novel yang bisa dikatakan hadir pada momen tepat dengan takaran pas dari segi tematik. Novel ini semacam fabel kontemporer yang menyajikan tema terkait isu sangat urgen pada masa kini, yakni isu ekologi. Dengan menempatkan lautan sebagai latar dan ikan remora kecil sebagai narator, novel menggelitik pembaca untuk melakukan kontemplasi ulang terkait relasi antara manusia dengan lingkungan. Secara lebih spesifik lagi relasi antara manusia dengan apa yang oleh Helen Czerski disebut sebagai Mesin Biru, kekayaan alam Indonesia yang, setelah lama terlantar, kembali mendapat perhatian kembali belakangan ini, baik disebabkan oleh kesadaran akan nilai penting relasi tersebut ataupun sekadar didorong oleh memori akan kejayaan maritim di masa lampau.
Menjelajahi dunia novel kontemporer kita dan berakhir, untuk sementara, dengan memutuskan memilih kelima novel ini sebagai representasi novel kita selama satu tahun terakhir, kami menemukan keluasan tema dan cara penyajian yang disajikan oleh para novelis, baik pemula ataupun yang sudah memiliki rekam jejak panjang. Terlepas dari karakteristik negatif zaman kontemporer yang sudah disinggung di awal, perkembangan teknologi juga memudahkan penerbitan novel dan akses atas berbagai informasi terbaru, dua hal yang dengan sentuhan kreatif seorang pengarang idealnya mampu memproduksi novel yang menjanjikan.
Namun, di tengah potensi positif tersebut, tak terhindarkan tetap hadir berbagai fenomena warisan, termasuk tegangan antara sifat lokusi dan perlokusi sebuah novel. Tegangan semacam itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan debat kusir, melainkan membutuhkan ketulusan untuk bersama-sama kembali pada satu dari sekian prinsip yang pernah ada dalam naratologi. Saat persoalan ini mengemuka, kami berpegang pada prinsip bahwa sebuah novel pertama-tama dan terutama adalah sebuah novel, bahwa sebuah novel bukan merupakan gelanggang tempat oposisi biner berperang, melainkan sebuah ruang dialektika antara makna tekstual dan makna referensial.
Dengan kata lain, kelima novel di atas dipilih pertama-tama dan terutama berdasarkan jelajah anasir intrinsiknya sebagai novel, bukan karena pertimbangan anasir ekstrinsik apa pun. Dari prinsip tersebut, keragaman pun terutama tampak pada segi tema dan gaya penulisan novel. Adapun keragaman anasir ekstrinsik yang juga hadir, baik itu terkait penerbit ataupun latar belakang, gender, dan rekam jejak pengarang, percayalah bahwa keragaman tersebut hadir sebagai tambahan, tanpa kesengajaan.
Selanjutnya, novel terbaik yang kami pilih menampilkan kisah yang menempatkan jelajah batin karakter-karakternya sebagai poros. Kesegaran hadir dalam tema yang berlapis sehingga menampilkan karakter yang tidak tunggal nilai didukung oleh cara bercerita yang mewakili keberagaman suara naratif. Penulis secara sadar memilih peristiwa-peristiwa yang merupakan metafora getirnya hubungan manusia dengan alam.
MENGOLAH PERANGKAT PUITIK UNTUK PUISI
Pertimbangan terhadap buku-buku puisi pilihan Kusala Sastra Khatulistiwa 2025 berkisar pada diskusi atas beberapa pertanyaan.
Pertama, apakah perpuisian kita belakangan telah menunjukkan tanda-tanda arah baru yang menjanjikan cakrawala lain penciptaan? Cara yang agaknya paling mudah untuk mulai menelisiknya barangkali dengan memperhatikan tumbuhnya keberagaman ucap dan tema, yang makin subur dalam perkembangan situasi sosial budaya kita saat ini, sekaligus ditunjang oleh iklim penerbitan yang berpegang pada kurasi khasnya masing-masing. Ini memberikan corak amat menarik, yang andai kita memandangnya dari kejauhan akan tampak serupa sebaran akar-akar yang menjulur dengan jalannya sendiri; ada yang menukik makin dalam ke celah tanah, ada yang menyisir ke permukaan dan gampang dijangkau siapa saja, ada yang membelit ke benda-benda dan membentuk suatu rupa yang mungkin tampak asing.
Maka demikianlah daftar panjang kategori puisi disusun sebagai sebuah lanskap dari apa yang kita miliki hari ini. Kita masih dapat melihat adanya elaborasi kreativitas yang setia mengolah metafora dan perangkat puitika, kehendak untuk mengeksplorasi cara tutur atau kelisanan, hingga menantang kemungkinan puisi dalam memaknai ulang wacana yang ada di masyarakat. Strategi-strategi penciptaan ini sangat mungkin menjadi tunas baru, meski mana di antaranya yang akan berumur panjang dan lestari diikuti oleh generasi berikutnya, hanya akan bisa dijawab oleh waktu.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana si penyair menggunakan puisinya sebagai reaksi atas tegangan-tegangan kreatif yang bersumber dari dalam maupun luar dirinya? Hal ini kiranya cukup relevan diajukan agar kita selalu memiliki kesempatan untuk menafsir ulang makna puisi dalam kehidupan kita sehingga ia tidaklah hadir sebagai sebuah entitas yang berjarak. Kendati begitu, respons kreatif itu mau tak mau perlu diperbandingkan dan ditimbang ulang lagi dengan kepekaan mengolah perangkat bahasa sebagai usaha menghargai keberaksaraan puisi, atau adakah tanggapan-tanggapan itu sudah cukup sering dilakukan oleh penyair lain maupun oleh si penyairnya sendiri.
Diskusi pada poin ini tak termungkiri beririsan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terperinci dalam membaca sajak per sajak dan bukan secara selayang pandang sebuah buku. Tanpa bermaksud meniadakan yang umum karena hendak menilik yang khusus, ini kiranya semata dorongan untuk memperhatikan keteguhan sikap sang penyair, baik terhadap tema yang dipilihnya, bahasa yang diolahnya, maupun dunia yang mau dibangunnya dalam buku puisi yang ditulisnya. Dan tidak termungkiri pula, ini menimbulkan debat yang seru di kalangan para juri dan boleh dibilang nyaris tidak ada suara yang cukup solid dalam memilih bahkan untuk daftar pendek.
Walau demikian, pilihan daftar pendek akhirnya ditetapkan juga dan ditulis secara urutan acak, yaitu Hantu Padang karya Esha Tegar Putra, Nyawa Tinggallah Sejenak Lebih Lama karya Pranita Dewi, Dengung Tanah Goyah karya Iyut Fitra, Syekh Siti Jenar dan Sepinggan Puisi dalam Kobaran Api karya Syaiful Alim, dan Tilas Genosida karya A. Muttaqin.
Dengan menggunakan penomoran sebagai judul puisi, Hantu Padang, yang mengolah beragam objek tanpa terkurung pola-pola umum lirisisme, menghimpun puisi-puisi yang berdiri sendiri, tapi saling menyambung, merangkai elegi panjang yang menghamparkan lanskap emosional pada setiap bagiannya. Kepulangan penuh luka ke kota yang memeram trauma hadir melalui imaji yang padat dan khas. Masa lalu dengan segenap kenangan dan ingatan buruk selalu bangkit tiap kali aku lirik terhubung kembali dengan objek yang sama; objek alam, makanan, bunyi dan musik, bahkan objek mistis seperti mantra dan kuburan lama. Hal tersebut melahirkan ketegangan puitik yang disikapi aku lirik tanpa melodramatik. Penyair mampu menahan diri untuk tidak berlarat-larat dalam sentimentil atau keharuan yang berlebihan.
Penggarapan bentuk yang ketat, namun cukup cair adalah hal baik karena bahasa tidak dilihat penyairnya sebagai sesuatu yang menegangkan. Teknik-teknik puitik seperti metafora, metonimia, catachresis, simile, personifikasi, simbol, berbagai jenis citraan, rima, dan sebagainya, dikuasai penyair dengan matang, lalu digunakan secara tangkas, lincah, dan cermat untuk membangun puisi-puisi yang kuat dalam rasa dan bentuk pada buku ini.
Sementara itu, tiga puluh puisi dalam Nyawa, Tinggallah Sejenak Lebih Lama menghadirkan keragaman tema dan sudut pandang yang tak tunggal atas berbagai persoalan. Suara-suara yang lahir dari aku lirik pun muncul dalam wujud yang beragam—dari makhluk mitologi, pahlawan, tokoh fiksi, hingga sosok-sosok anonim. Mereka membawa kisah, menggenggam luka, dan memeram kegelisahan. Kelahiran dan kematian, ketegangan relasi, baik dengan Tuhan, alam, maupun sesama manusia, berulang kali muncul sebagai gema yang menggugah. Tak jarang, persoalan-persoalan itu disambut dengan respons yang getir, bahkan dramatik oleh para aku lirik.
Secara umum, penyair cukup piawai menggunakan teknik-teknik puitik seperti alegori, ironi, oksimoron, personifikasi, metafora, dan simbolisme untuk membangun puisi-puisinya, juga cermat menyisipkan bentuk repetisi seperti anaphora dan epizeuksis demi memperkuat daya sugestif puisi, sekaligus menegaskan bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dalam struktur balada, epik, monolog dramatis, maupun jenis puisi lainnya yang termuat dalam buku ini.
Dengung Tanah Goyah secara ajek menghadirkan dunia buruk rupa dengan segala problemnya. Tema seputar penyalahgunaan kekuasaan, keegoisan manusia, kerusakan alam hingga kerusakan puisi tergarap dengan rapi, mendalam dan tuntas dalam puisi-puisi pada buku ini. Subjek orang ketiga tunggal, “ia”, sebagai yang didera berbagai derita fisik dan batin di dunia buruk rupa, ditampilkan penyair sebagai sosok yang bereaksi tidak berlebihan. Penyair cukup mampu menahan diri dengan membiarkan sang “ia” melihat, menyulut api dan menjaganya, lalu terus berjalan, setelah atau sambil mencatat, dengan atau tanpa menyeka air mata. Penyair kuasa mengekang hasrat untuk mengomentari, menyinyiri, menghakimi, apalagi membuat definisi-definisi yang bikin puisi menjadi cerewet dan berisik. Keheningan yang tetap mendapat tempat di tanah yang goyah dan diriuhi dengung menciptakan keseimbangan suasana puitik yang apik.
Baris dan bait dalam 41 puisi yang terkumpul dalam Dengung Tanah Goyah memuat rangkaian diksi yang merepresentasikan warna dan situasi dunia yang hendak dihadirkan oleh penyair. Dengan terampil penyair merangkai pilihan kata konkret dan abstrak menjadi metafora, simile, dan personifikasi yang tidak sekadar menginformasikan suasana lahir dan batin subjek puisi, tetapi juga menghidupkannya secara intens melalui citraan dan nuansa emosional. Di samping itu, penyair secara konsisten menyisipkan bentuk repetisi serta kutipan sebagai bagian bait pada hampir seluruh puisi dalam buku ini.
Selaras dengan judulnya, Syekh Siti Jenar dan Sepinggan Puisi dalam Kobaran Api ini memiliki dua bagian yang secara garis besar menawarkan cara lain dalam melihat sosok yang selama ini telah lekat dengan mitos. Pada bagian pertama, penyair menghadirkan tokoh yang spesifik, yakni Syekh Siti Jenar. Di bagian ini (dalam buku dikelompokkan sebagai suhuf pertama) secara historis, penyair membuat perhitungan-perhitungan baru terhadap yang lama, yang memang tidak menempati wacana arus utama dalam perbincangan. Sementara pada bagian kedua, penyair menghadirkan tokoh-tokoh anonim. Jenarisme digunakan penyair sebagai sarana dialektika dan mengkritik kondisi saat ini, khususnya situasi masyarakat yang berpandangan kaku nyaris beku terhadap agama.
Buku ini cukup berhasil mengangkat tema religiusitas tanpa terjebak dalam banalitas dakwah, berkat keberhasilan penyair menjaga kualitas puitiknya. Ragam nada—dari sinis, jenaka, melankolis, hingga sentimentil—menghidupkan puisi-puisi dengan pendekatan yang beragam. Kekayaan diksi, mulai dari bahasa Jawa hingga bahasa gaul, dimanfaatkan untuk membangun citraan, metafora, dan bentuk-bentuk repetisi dalam struktur puisi yang bervariasi.
Terbagi ke dalam dua bagian utama yang masing-masing dipecah lagi menjadi dua subbagian, Tilas Genosida memuat 29 puisi dengan cara ungkap, sudut pandang, dan persoalan yang cukup heterogen. Dengan keberpihakan yang jelas terhadap yang lemah dan terpinggirkan, penyair meramu berbagai objek, rujukan, serta topik-topik besar yang sudah jamak dikenal. Bagian pertama buku ini menyuguhkan kearifan yang terkandung dalam rahim alam: objek-objek yang akrab dengan kehidupan petani seperti padi, pedati, dan sungai dihidupkan menjadi subjek yang menyuarakan nilai-nilai kebijaksanaan dengan tenang dan jernih. Setelah subbagian ini, puisi-puisi yang menghadirkan dunia santri, rumah tangga, hingga ruang bar hadir secara bergantian, membawa tema-tema seputar religiusitas, spiritualitas, kematian, asmara, dan isu kemanusiaan
Secara umum, perangkat puitik seperti metafora, aliterasi, repetisi, dan citraan digunakan penyair dengan terampil untuk membangun dunia putiknya. Tampak pula jejak pencarian ekspresi yang dinamis, antara lain melalui strategi menjadikan objek-objek puitik sebagai subjek yang menyuarakan permenungan maupun persoalan sosial. Penyair juga menunjukkan keberanian menjelajah di luar konvensi puisi liris dan naratif, serta bereksperimen dengan menyisipkan baris-baris yang memuat pertentangan makna sebagai cara membangun ketegangan dalam teks.
Buku puisi terbaik yang kami pilih mengolah beragam objek tanpa terkurung pola umum lirisisme, menghimpun puisi-puisi yang berdiri sendiri, tapi saling menyambung, merangkai elegi panjang yang menghamparkan lanskap emosional pada setiap bagiannya. Kepulangan penuh luka ke kota yang memeram trauma hadir melalui imaji yang padat dan khas. Masa lalu dengan segenap kenangan dan ingatan buruk selalu bangkit tiap kali aku lirik terhubung kembali dengan objek yang sama; objek alam, makanan, bunyi dan musik, bahkan objek mistis seperti mantra dan kuburan lama. Hal tersebut melahirkan ketegangan puitik yang disikapi aku lirik tanpa melodramatik. Penyair mampu menahan diri untuk tidak berlarat-larat dalam sentimental atau keharuan yang berlebihan.
Berdasarkan hal di atas, buku pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa 2025:
- Kategori Cerpen diraih oleh Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-kupu karya Sasti Gotama.
- Kategori Novel diraih oleh Duri dan Kutuk karya Cicilia Oday.
- Kategori Puisi diraih oleh Hantu Padang karya Esha Tegar Putra.
Selamat kepada para pemenang.
Dewan Juri Kusala Sastra Khatulistiwa 2025
Ketua: Djoko Saryono
Anggota:
- Kurnia Effendi
- Asep Subhan
- Ni Made Purnama Sari
- Inggit Putria Marga

https://www.youtube.com/watch?v=UqfcchhswrU&t=2120s
Unduh Buku Program Kusala Sastra Khatulistiwa 2025
Daftar Pendek Kusala Sastra Khatulistiwa 2025
Jakarta, 16 Juni 2025 — Yayasan Richard Oh Kusala Indonesia (YRKI) memulai rangkaian penyelenggaraan Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) tahun ini dengan menunjuk tiga orang kurator: Eka Kurniawan, Hasan Aspahani, dan Nezar Patria. Selanjutnya, melalui Konferensi Pers yang dilaksanakan pada bulan Januari lalu, KSK secara resmi dinyatakan diselenggarakan kembali. Tahapan demi tahapan penjurian telah dilaksanakan dan sampailah kita pada Daftar Pendek KSK 2025.
Kusala Sastra Khatulistiwa adalah penghargaan bagi karya sastra terbaik sepanjang tahun, yang menunjukkan pengerahan kerja kreatif sastrawan Indonesia, pengembangan potensi estetis dalam penggunaan bahasa Indonesia, dan perluasan kemungkinan wilayah pertemuan antara imajinasi dan realitas kehidupan masyarakat Indonesia.
Buku-buku yang dinilai adalah buku-buku yang diterbitkan sepanjang tahun 2024, terbagi dalam tiga kategori: Kumpulan Cerpen, Novel, dan Kumpulan Puisi. Pelaksanaan KSK tahun ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dana Indonesiana, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Berikut adalah keputusan Dewan Juri Kusala Sastra Khatulistiwa 2025.
Daftar Pendek Kusala Sastra Khatulistiwa 2025
Kategori Kumpulan Cerpen
- Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-kupu karya Sasti Gotama
- Iblis Tanah Suci karya Arianto Adipurwanto
- Keluarga Oriente karya Armin Bell
- Mei Salon karya Iin Farliani
- Musik Akhir Zaman karya Kiki Sulistyo
Kategori Kumpulan Puisi
- Dengung Tanah Goyah karya Iyut Fitra
- Hantu Padang karya Esha Tegar Putra
- Nyawa, Tinggallah Sejenak Lebih Lama karya Pranita Dewi
- Syekh Siti Jenar dan Sepinggan Puisi dalam Kobaran Api karya Syaiful Alim
- Tilas Genosida karya A. Muttaqin
Kategori Novel
- BEK Karya Mahfud Ikhwan
- Duri dan Kutuk karya Cicilia Oday
- Matthes karya Alan TH
- Oni Jouska karya Asep Ardian
- Paya Nie karya Ida Fitri
Daftar Pendek ini disusun berdasarkan urutan abjad.

Daftar Panjang Kusala Sastra Khatulistiwa 2025
Jakarta, 17 Mei 2025 -- Setelah tidak hadir selama tiga edisi, Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) kembali hadir di tahun 2025 ini. Bermula dari gagasan pemilik toko buku, penulis, sekaligus sutradara film Richard Oh, penghargaan sastra ini telah berlangsung sejak 2001. Kehadirannya tak hanya merayakan pencapaian-pencapaian dalam prosa dan puisi Indonesia, tapi juga memperkaya ekosistem perbukuan dan kesusastraan. Kusala Sastra Khatulistiwa 2025 diselenggarakan oleh Yayasan Richard Oh Kusala Indonesia, didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dana Indonesiana, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sebagaimana telah menjadi tradisi, pengumuman pemenang akan diselenggarakan dalam tiga tahap. Kami akan memulainya dari Daftar Panjang, kemudian Daftar Pendek, hingga terpilih satu pemenang di masing-masing kategori.
Hari ini kami dengan penuh rasa syukur mengumumkan Daftar Panjang berisi sepuluh judul buku untuk kategori Cerita Pendek, Puisi, dan Novel. Tim juri telah memilih dengan pembacaan cermat, juga perdebatan hangat. Mereka masih akan terus bekerja, membaca dengan lebih cermat untuk menentukan Daftar Pendek (lima judul buku tiap kategori). Ada jarak satu bulan dari pengumuman Daftar Panjang ke Daftar Pendek. Kami memang meminta juri untuk memberi ruang waktu agar publik bisa ikut menilai. Penerbit dan toko buku akan memiliki cukup waktu juga untuk mempromosikan buku-buku tersebut. Kami yakin inilah cara Kusala Sastra Khatulistiwa memberi sedikit dampak baik bagi ekosistem sastra kita secara keseluruhan, yaitu buku-buku yang baik terpromosikan dengan cukup dan sebanyak-banyaknya sampai di tangan pembaca.
Daftar Panjang di bawah ini adalah karya sastra terbaik untuk tahun ini, terpilih dari buku yang terbit sepanjang tahun lalu yang dinilai juri. Kami senang dapat mendukung munculnya karya-karya sastra terbaik. Kita berharap karya-karya sastra itu dapat memperkaya jiwa masyarakat Indonesia, serta dapat menjadi sumber inspirasi, semangat, dan harapan kita dalam memahami dunia yang berubah begitu cepat hari ini.
Selamat untuk para penulis buku-buku tersebut, dan selamat merayakan kesusastraan kita hari ini bagi kita semua.
Tim Kurator Kusala Sastra Khatulistiwa
Eka Kurniawan
Hasan Aspahani
Nezar Patria
Daftar Panjang Kategori Kumpulan Cerpen*
- Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-kupu karya Sasti Gotama
- Cerobong Tua Terus Mendera karya Raudal Tanjung Banua
- Iblis Tanah Suci karya Arianto Adipurwanto
- Kebun Jagal karya Putra Hidayatullah
- Keluarga Oriente karya Armin Bell
- Mei Salon karya Iin Farliani
- Musik Akhir Zaman karya Kiki Sulistyo
- Musim di Rambut Ibu karya Mashdar Zainal
- Pelayaran Terakhir karya Anggit Rizkianto
- Pengetahuan Baru Umat Manusia karya Ken Hanggara
Daftar Panjang Kategori Kumpulan Puisi*
- CICA 96 Puisi Cyntha Hariadi karya Cyntha Hariadi
- Dengung Tanah Goyah karya Iyut Fitra
- Ekphrasis karya Tan Lioe Ie
- Hantu Padang karya Esha Tegar Putra
- Hidup Tetap Berjalan dan Kita Telah Lupa Alasannya karya Ibe S. Palogai
- Jejak Lintasan karya Raudal Tanjung Banua
- Nyawa, Tinggallah Sejenak Lebih Lama karya Pranita Dewi
- Selamat Malam, Kawan! karya Muhaimin Nurrizqy
- Syekh Siti Jenar dan Sepinggan Puisi dalam Kobaran Api karya Syaiful Alim
- Tilas Genosida karya A. Muttaqin
Daftar Panjang Kategori Novel*
- Ajengan Anjing karya Ridwan Malik
- BEK: Sebuah Novel karya Mahfud Ikhwan
- Duri dan Kutuk karya Cicilia Oday
- Ingatan Ikan-ikan karya Sasti Gotama
- Inyik Balang karya Andre Septiawan
- Mari Pergi Lebih Jauh karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie
- Matthes karya Alan TH
- Oni Jouska karya Asep Ardian
- Paya Nie: Sebuah Novel karya Ida Fitri
- Taksi Malam karya T. Agus Khaidir
*Urutan berdasarkan abjad, bukan peringkat.
---Selesai---
Panggilan Terbuka Kusala Sastra Khatulistiwa 2025
Pada tahun 2001, seorang penulis, pemilik toko buku, dan sutradara film Richard Oh, memiliki gagasan untuk menghadirkan sebuah penghargaan sastra yang kemudian ia beri nama Khatulistiwa Literary Award. Nama ini berubah di tahun 2014, setelah mempertimbangkan banyak hal, termasuk untuk lebih konsisten mempergunakan bahasa Indonesia, menjadi Kusala Sastra Khatulistiwa. Melalui tangan dinginnya, juga kegigihannya menghadapi berbagai rintangan termasuk pandemi Covid 19, penghargaan ini terus berlangsung setiap tahun.
Sejumlah nama sastrawan Indonesia pernah mendapatkan penghargaan tersebut, baik untuk kategori prosa maupun puisi. Seno Gumira Ajidarma, Linda Christanty, Goenawan Mohamad, Hamsad Rangkuti, Acep Zamzam Noor, Nirwan Dewanto, Kiki Sulistyo, Ayu Utami, Joko Pinurbo, Afrizal Malna, Okky Madasari, Iksaka Banu, Leila S. Chudori, Inggit Putria Marga, Aan Mansyur dan banyak nama lainnya pernah naik ke panggung penghargaan ini, yang biasanya dilaksanakan di Plaza Senayan, Jakarta.
Kabar duka datang di tahun 2022, ketika Richard Oh, sang penggagas dan motor utama penghargaan ini meninggal. Pada tahun itu, Kusala Sastra Khatulistiwa berhenti. Di tahun berikutnya, pembicaraan mengenai pentingnya menghadirkan kembali Kusala Sastra Khatulistiwa mulai terdengar di antara orang-orang terdekat Richard Oh maupun dari komunitas sastra yang lebih luas.
Digerakkan oleh istri Richard, Pratiwi Juliani, dan adiknya, Linda Oh, Yayasan Richard Oh Kusala Indonesia (YRKI) didirikan tahun 2024. Lembaga ini berinisiatif meneruskan apa yang telah dibangun oleh semangat filantropis dan kecintaan terhadap kesusastraan dari seorang Richard Oh.
Dengan dukungan Dana Indonesiana serta sejumlah sponsor lain, YRKI menghadirkan kembali Kusala Sastra Khatulistiwa di tahun 2025 ini. Yayasan telah menunjuk tiga orang kurator program yaitu Nezar Patria, Eka Kurniawan, dan Hasan Aspahani.
Ada beberapa hal baru dalam penyelenggaraan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun ini. Penghargaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu untuk buku puisi, novel, dan cerpen.
Pembagian ini diputuskan untuk memberi ruang berkembang yang lebih besar pada cerpen yang memiliki perkembangan sangat penting dalam tradisi sastra Indonesia. Buku-buku yang dinilai adalah karya berbahasa Indonesia yang terbit sepanjang tahun 2024.
Hal lain yang juga baru adalah tambahan hadiah berupa pembelian buku pemenang senilai Rp25 juta. Buku akan disebarkan ke sekolah, komunitas, dan perpustakaan/taman bacaan masyarakat, sebagai dukungan pada penerbit, serta perluasan pembaca karya sastra yang berkualitas. Adapun hadiah untuk tiga buku terbaik masing-masing Rp75 juta. Dengan demikian maka total nilai hadiah masing-masing pemenang menjadi Rp100 juta
Syarat dan Ketentuan
- Terbuka bagi penulis berkewarganegaraan Indonesia. Karya yang diajukan merupakan hasil karya penulis tunggal dan tidak melanggar hak cipta.
- Karya yang diajukan berupa buku cetak yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2024.
- Karya ditulis dalam bahasa Indonesia.
- Tiga kategori karya:
-
- Kumpulan cerpen, dengan jumlah minimal dua cerpen.
- Novel, dengan panjang minimal 30.000 kata.
- Kumpulan puisi, yang terdiri dari minimal 40 puisi, atau 40 halaman, atau satu puisi panjang dengan total minimal 40 halaman.
- Penerbit atau penulis mengirimkan setidaknya dua eksemplar dari setiap judul karya yang diajukan. Pengiriman disertai dokumen pendukung berupa biodata penulis dan mencantumkan informasi kontak.
- Karya dikirimkan paling lambat tanggal 20 Februari 2025 (cap pos). Karya dikirimkan ke:
Kusala Sastra Khatulistiwa 2025
ED Cluster No. 2A
Jalan Gunung Indah V
Cirendeu, Ciputat Timur,
Tangerang Selatan, Banten
15445
- Daftar panjang dan daftar pendek karya terpilih diumumkan sebelum pengumuman pemenang.
- Pengumuman pemenang akan dilakukan pada acara Malam Anugerah Kusala Sastra Khatulistiwa 2025.
Narahubung
Email: info@kusala.id